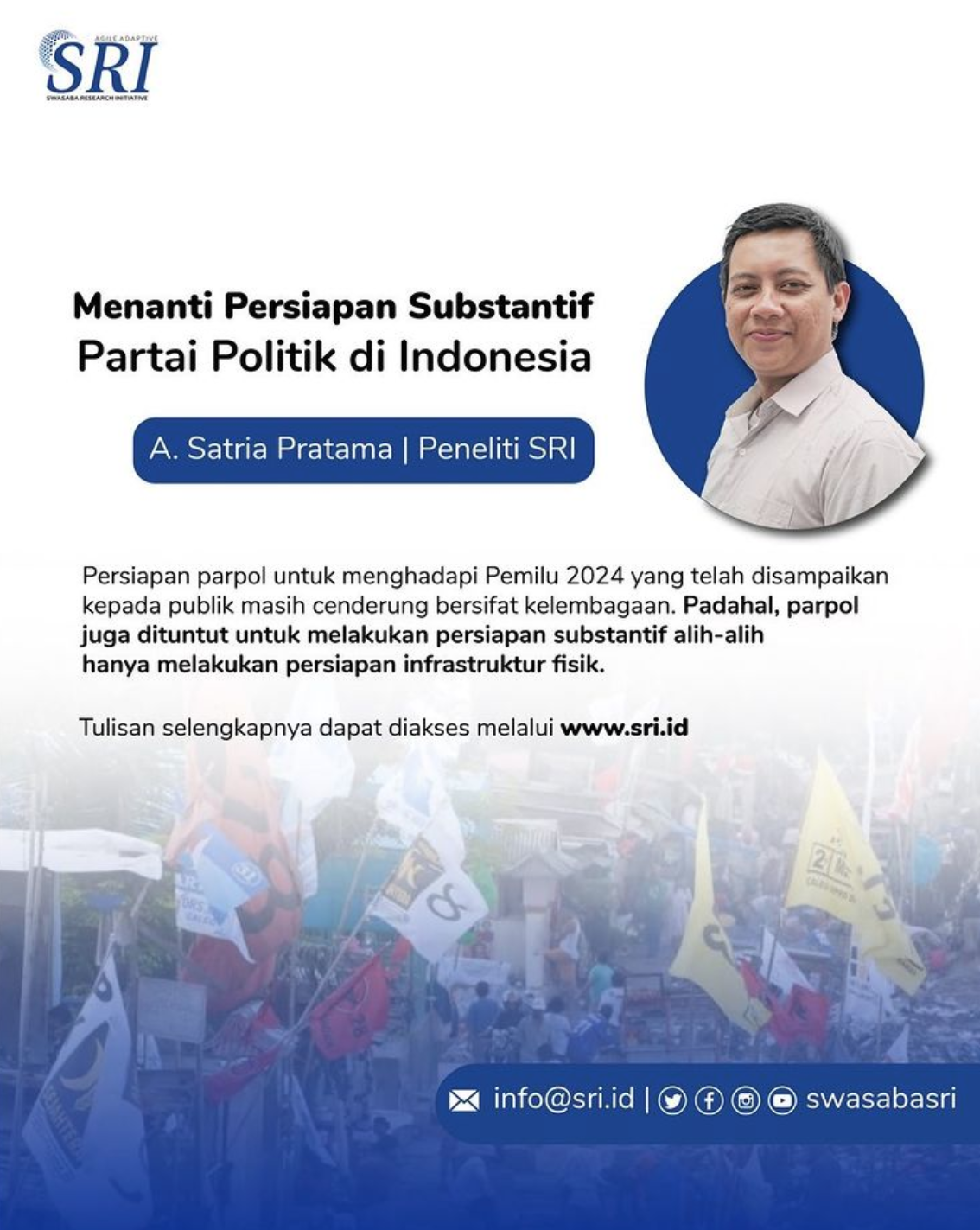Oleh: Hilman Gufron
Dosen Polban
Bayangkan sebuah pasar politik di mana semua pedagang menawarkan barang serupa, tanpa label harga atau kualitas yang jelas. Itulah gambaran partai politik Indonesia saat ini. Di tengah hiruk-pikuk Pemilu 2024 dan koalisi raksasa di bawah pemerintahan Prabowo Subianto, partai-partai seolah kehilangan arah: nasionalis, Islamis, atau sekuler? Sosialis atau liberal? Semua melebur, didorong ambisi kekuasaan dan figur populer. Ketidakjelasan ideologi ini bukan sekadar kelemahan administratif, melainkan krisis identitas yang menggerus kepercayaan publik dan melemahkan demokrasi. Survei Celios 2025 menunjukkan hanya 40% pemilih muda merasa terwakili oleh partai mana pun.
Sejarah partai politik Indonesia dimulai dengan semangat ideologis kuat pasca-kemerdekaan. Maklumat X tahun 1945 membuka ruang bagi partai berbasis aliran: nasionalis seperti PNI Soekarno, Islamis seperti Masyumi, sosialis seperti PSI, hingga komunis seperti PKI. Pancasila menjadi payung, namun perbedaan ideologi jelas: nasionalis menekankan kesatuan bangsa, Islamis peran agama, dan sosialis keadilan ekonomi. Era Orde Baru mengubah segalanya dengan asas tunggal Pancasila, menyederhanakan partai menjadi Golkar, PPP, dan PDI. Reformasi 1998 membuka multipartai, tetapi warisan pragmatisme bertahan. Kini, dengan 18 partai nasional, ideologi hanya retorika di anggaran dasar, sementara praktiknya didominasi koalisi “pelangi” yang mengabaikan prinsip. Jurnal JIIP menyebut partai Indonesia “nirkonsistensi”, fokus pada kekuasaan jangka pendek ketimbang visi jangka panjang.
Dominasi
Ideologi partai sering kali kalah oleh kekuatan karisma seorang pemimpin. Pemilih lebih terikat pada tokoh seperti Jokowi atau Prabowo, sehingga partai dianggap sebagai “kendaraan” sementara. Pada 2025, PSI yang dipimpin Kaesang Pangarep melakukan perubahan identitas dengan logo gajah yang melambangkan “solidaritas”, tetapi mendapat kritik karena kurang jelas dan tanpa dasar ideologis yang kuat. Partai-partai bergabung dalam koalisi besar demi mendapatkan kursi menteri, meskipun ideologinya saling bertentangan—misalnya, PKS yang Islamis bermitra dengan PDIP yang nasionalis sekuler. Akibatnya, polarisasi hanya muncul dalam isu agama, namun tidak jelas dalam masalah ekonomi, di mana semua partai menawarkan infrastruktur dan subsidi yang serupa. Edward Aspinall menyebut partai Indonesia sebagai “kartel” yang membagi kekuasaan, bukan sebagai tempat persaingan ideologis.
Banyak kader yang naik pangkat karena dekat dengan elit atau dana, bukan karena pemahaman terhadap ideologi. Seminar Nasional Refleksi Delapan Dekade Demokrasi menyoroti ketidakdisiplinan internal: DPP partai tidak mampu mengkoordinasikan kebijakan, menyebabkan perselisihan antar kader dan visi yang tidak jelas. Contohnya, Gerindra yang lahir dari militerisme nasionalis, kini bersikap fleksibel dalam mendukung kebijakan neoliberal seperti Omnibus Law Cipta Kerja, yang dikritik oleh sosialis. Survei Celios 2025 menunjukkan bahwa 60% kader muda tidak memahami ideologi partai mereka, memperparah krisis identitas.
Pembuatan kebijakan dan undang-undang akan lebih komprehensif jika partai memiliki ideologi kiri-kanan yang jelas. Bayangkan debat subsidi BBM 2025: partai kiri dengan hipotetis seperti Partai Buruh akan mempertahankan subsidi Rp 250 triliun untuk melindungi pekerja, didanai pajak progresif, dengan argumentasi data BPS bahwa kenaikan BBM menambah 2 juta orang miskin. Partai berideologi kanan akan mendorong bantuan langsung tunai dan investasi swasta untuk efisiensi, merujuk data Kemenkeu bahwa 60% subsidi salah sasaran. Isu lain seperti upah minimum regional (UMR) versus investasi asing juga menunjukkan potensi diskursus ideologi. Partai kiri akan menuntut kenaikan UMR 15% untuk melindungi 50 juta pekerja informal, seperti yang diusulkan serikat buruh di Jakarta 2025, dengan alasan inflasi 7% meningkatkan biaya hidup. Partai kanan akan menentang, mengutip data Kadin bahwa kenaikan UMR bisa kurangi investasi asing sebesar 10%, merujuk keberhasilan Vietnam menarik FDI dengan upah kompetitif. Di Inggris, debat pajak warisan 2024 antara Partai Labour yang mendukung redistribusi dan Partai Konservatif yang pro-pasar bebas memaksa kebijakan terukur dengan data ONS. Di Indonesia, koalisi raksasa 2025 melemahkan oposisi sehingga UU seperti Inpres No. 1/2025, yang menyebabkan PHK 250.000 pekerja, lolos tanpa kritik ideologis, memicu demo #ResetSystem. Ideologi yang jelas akan menciptakan parlemen yang hidup, bukan sekadar stempel pemerintah.
UU Partai Politik (No. 2/2011, direvisi 2023) mewajibkan Pancasila sebagai asas, tetapi tidak memaksa diferensiasi ideologis, mendorong konvergensi ideologi. Studi UGM tentang UU KUHP dan Cipta Kerja menunjukkan partai oposisi menolak ide penguasa karena posisi kekuasaan, bukan karena prinsip. Di era Prabowo, koalisi 80% kursi DPR membuat oposisi minim, menghapus debat ideologis. Ini menciptakan kondisi “politik minus ideologi”, menurunkan partisipasi pemilu menjadi 70% dari 81% pada 2019.
Dampak
Ketidakjelasan ideologi berdampak luas. Partisipasi menurun karena hanya 40% pemilih muda merasa terwakili. Oportunisme mendominasi: partai mengabaikan konstituen demi kekuasaan, seperti dalam UU Inpres No. 1/2025 yang memicu PHK massal. Krisis identitas juga nyata: sengkarut konflik partai menunjukkan ideologi ambigu memicu kontradiksi. Akar masalahnya, demokrasi melemah—indeks demokrasi Indonesia turun ke 6.5 pada 2025 menurut Freedom House, karena partai gagal menjadi jembatan rakyat-pemerintah.
Untuk memulihkan demokrasi, segera reformasi UU, wajibkan partai publikasikan manifesto ideologis tahunan, seperti usul dari Lex Renaissance. Kaderisasi harus diperkuat dengan pendidikan ideologi wajib, mengadopsi model sekolah politik Eropa. Diferensiasi ideologi perlu didorong atas partai programatik, mengambil inspirasi dari sintesis Sukarno-Hatta soal nasionalisme dan keadilan sosial. Masyarakat juga harus berperan melalui kampanye literasi politik, mendorong pemilih memilih berdasarkan ide, bukan tokoh.
Ketidakjelasan ideologi partai politik bukan nasib, melainkan pilihan yang bisa diubah. Saatnya menuntut partai dengan visi jelas, prinsip kuat, dan perwakilan aspirasi sejati. Dari diskusi publik hingga kotak suara, suarakan ideologi yang nyata—bukan janji kosong. Bukankah itu esensi politik yang benar-benar merdeka?***